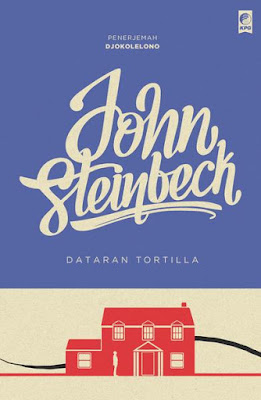Kehidupan harian di kota (besar) melahirkan
pengeluh-pengeluh. Saya salah satunya. Mungkin anda juga berada dalam satu
perahu yang sama dengan saya.
Lagi pula, apa yang tersisa bagi manusia kota yang selalu dihajar rutinitas harian, selain kesempatan untuk mengucap keluhan-keluhan yang semakin hari, semakin bertambah variatif itu?
Indikator keberhasilan yang dikenal oleh manusia kota adalah produktivitas. Manusia kota baru boleh disebut berhasil melalui hari, apabila tugas dan tenggat kerjanya di hari itu dapat ia penuhi seluruhnya. Dengan begitu, pergerakan manusia kota dipatok ke dalam agenda-agenda. Tak boleh ada waktu yang terbuang sia-sia, tak boleh ada waktu luang yang tidak dicokoli agenda. Ketika selesai dari satu agenda, agenda lain telah siap membayang, minta diselesaikan. Pada posisi demikian, kehidupan kota dan agenda-agendanya dapat digambarkan sebagai jejeran sergapan-sergapan; manusia kota tidak pernah betul-betul lolos (dan lulus) dari sergapan demi sergapan tersebut.
Benny Hoed, seorang ahli semiotika, punya penjelasan berkenaan dengan kebiasaan mematok-matok waktu ke dalam agenda-agenda itu. Menurut Hoed, dengan mendasarkan uraiannya pada buku karangan Edward T. Hall, The Dance of Life (1983), kebudayaan yang terobsesi untuk mematok-matok waktu disebut kebudayaan monokronik. Kebudayaan monokronik memandang waktu sebagai benda yang dapat diatur dan diperjualbelikan. Pada masyarakat dengan kebudayaan ini, waktu harus dijadwalkan dengan jelas. Menurut Hoed, “… waktu menjadi material… dijadikan alat untuk memilah urusan mana yang penting dan mana yang tidak”. Akibatnya, “… waktu makin mengindividualkan manusia, mengendurkan ikatan antar-individu dalam masyarakat”. Uraian Hoed sesungguhnya menarik karena menunjukkan bahwa model penggunaan waktu menurut kebudayaan monokronik dapat membawa masyarakat kepada ujung yang ekstrem: keterasingan individu dari masyarakatnya. (Menurut saya, tesis ini tidaklah hiperbolis dan mendramatisasi. Jika mengingat kesendirian kita, para manusia kota, di tengah ramai, riuh, dan gemerlapnya kota, tesis Hoed malah makin mendekati kenyataan).